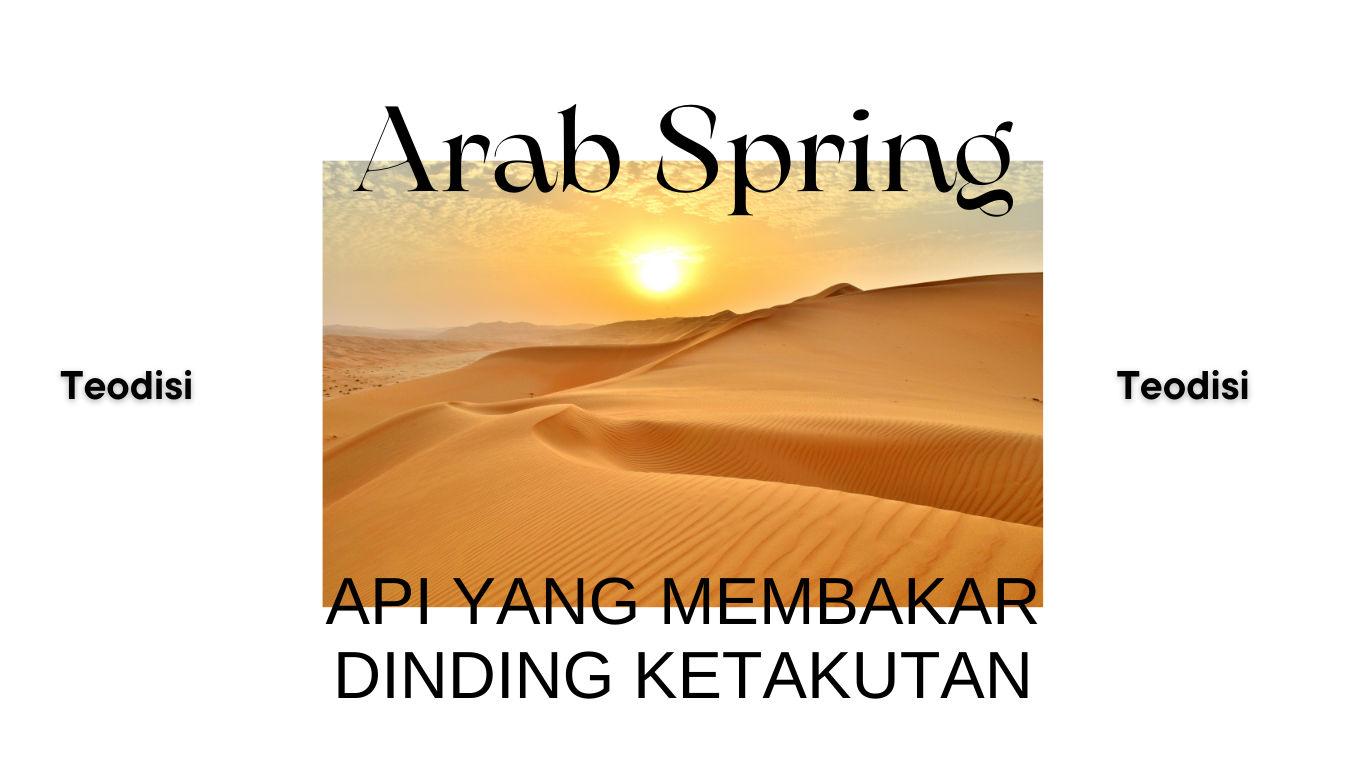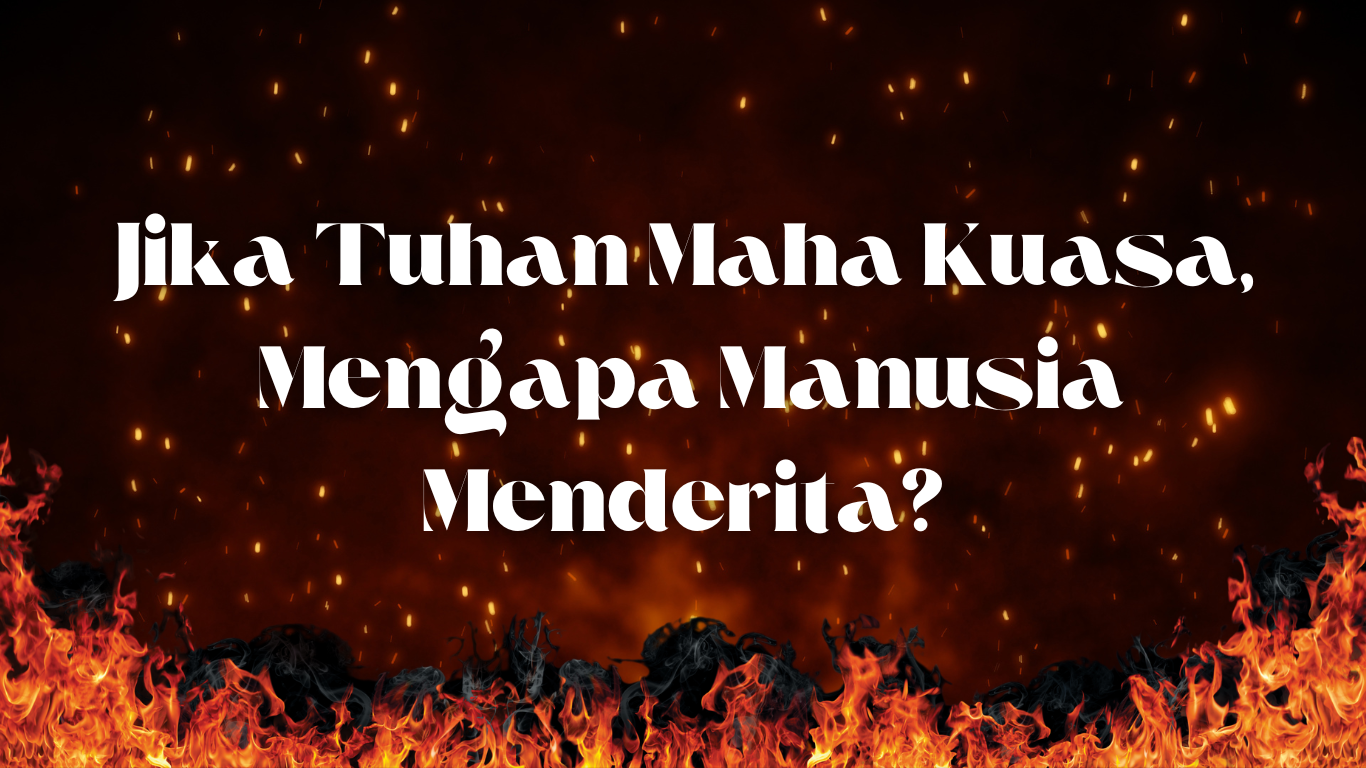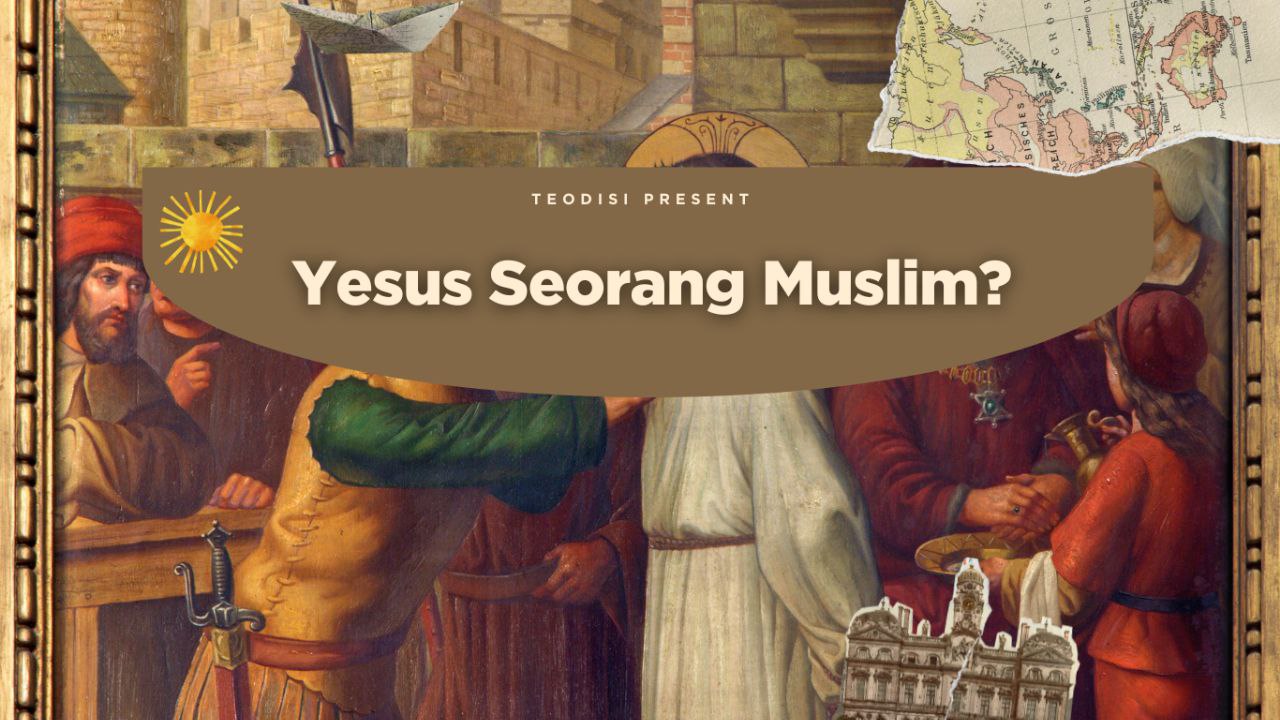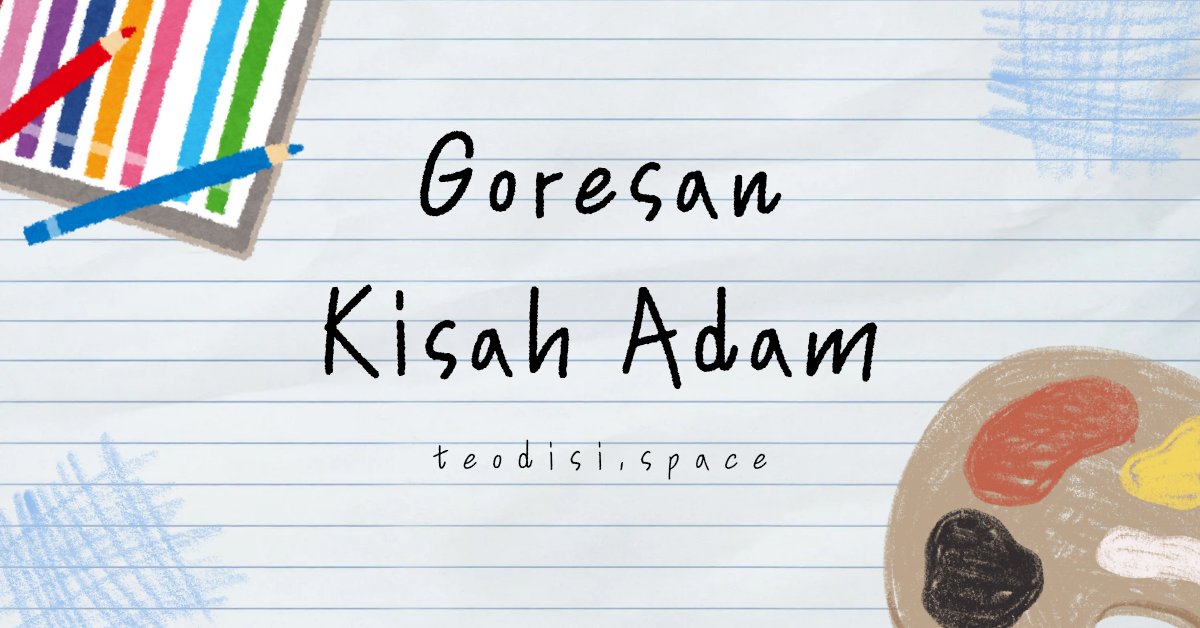Pada suatu pagi di bulan Desember 2010, di sebuah kota kecil bernama Sidi Bouzid, Tunisia, seorang pemuda bernama Mohamed Bouazizi menyalakan api pada dirinya sendiri. Ia bukan pejabat, bukan politisi, bukan pula aktivis besar. Ia hanya seorang penjual buah berusia 26 tahun, pencari nafkah untuk keluarganya. Tetapi tindakannya mengguncang dunia.
Hari itu, aparat kembali menyita dagangan Bouazizi dengan dalih perizinan. Ia dipermalukan di depan umum, bahkan ditampar oleh seorang pejabat perempuan. Saat ia mengadu ke pemerintah lokal, pintu keadilan ditutup rapat. Tidak ada ruang bagi suara rakyat kecil. Dalam keputusasaan yang gelap, Bouazizi memilih jalan tragis: tubuhnya sendiri dijadikan teriakannya.
Api itu membakar lebih dari sekadar seorang pemuda. Dalam hitungan hari, rakyat Tunisia turun ke jalan. Mereka berteriak menuntut keadilan, mengakhiri rezim korup, dan merebut martabat yang lama hilang. Satu bulan kemudian, Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang berkuasa lebih dari dua dekade tumbang. Dunia menyebutnya sebagai awal dari Arab Spring, gelombang revolusi yang merambat ke Mesir, Libya, Yaman, Suriah, dan melintasi batas negara.
Arab Spring adalah paradoks. Ia membuka pintu harapan, tapi juga menghadirkan luka panjang. Di Mesir, rakyat berhasil menggulingkan Hosni Mubarak, tetapi kemudian kembali diperintah dengan tangan besi. Di Libya, Muammar Gaddafi jatuh, tetapi negeri itu terjerumus dalam perang saudara. Suriah meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang masih berlangsung hingga kini.
Namun di balik semua kerumitan geopolitik itu, tetap ada sosok Bouazizi—simbol bahwa orang biasa bisa menjadi percikan sejarah. Ia tidak pernah berniat menjadi ikon global. Tetapi tindakannya menyuarakan jeritan universal: martabat manusia lebih berharga dari tirani.
Dalam tradisi Abrahamik, kisah Bouazizi mengingatkan kita pada benang merah ilahi: Allah membenci kezaliman. Nabi Musa berdiri di hadapan Firaun dengan tongkat sederhana. Nabi Isa menyentuh dan mengangkat kaum miskin yang terpinggirkan. Nabi Muhammad menegakkan keadilan sosial di tengah struktur Quraisy yang timpang. Semuanya menegaskan bahwa perlawanan pada ketidakadilan sering lahir bukan dari istana, melainkan dari orang-orang yang diremehkan.
Bouazizi memang wafat karena luka bakarnya. Tetapi kematiannya menghidupkan kesadaran baru: bahwa api keputusasaan bisa berubah menjadi api keberanian. Dunia mungkin bertanya-tanya, apakah revolusi yang lahir dari tindakannya berhasil membawa perubahan yang ia harapkan? Jawabannya belum selesai. Namun warisan Bouazizi bukanlah sekadar perubahan politik, melainkan kesaksian bahwa suara manusia, sekecil apa pun, tidak bisa dipadamkan selamanya.
Sejarah akhirnya meninggalkan kita pertanyaan: apakah kita akan menunggu ada Bouazizi lain yang membakar dirinya, ataukah kita berani menyalakan api keberanian sebelum ketidakadilan mengkremasi martabat manusia?
Penulis: Abqurah