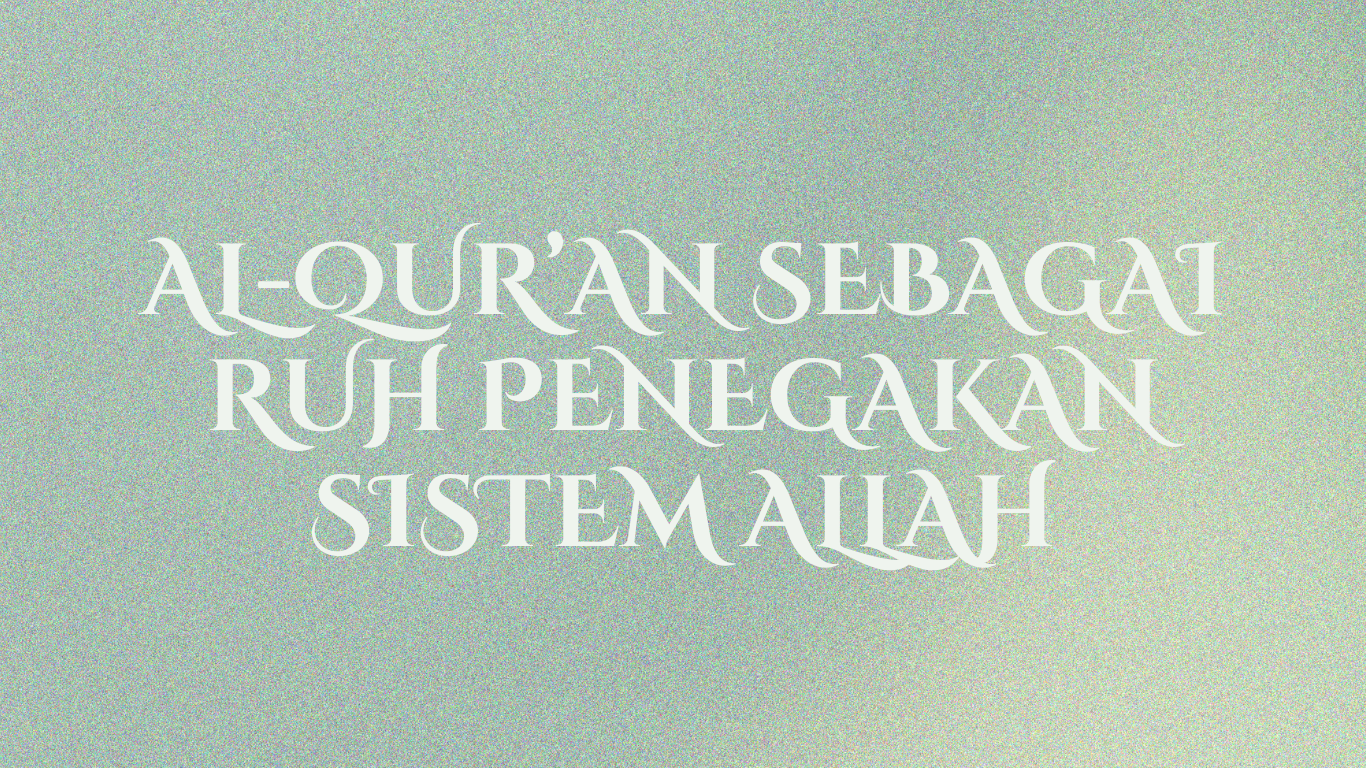Pada musim semi 1989, ribuan mahasiswa dan warga sipil berkumpul di Lapangan Tiananmen, Beijing. Mereka tidak membawa senjata, hanya spanduk, semangat, dan harapan. Tuntutan mereka sederhana sekaligus revolusioner: transparansi, akuntabilitas, kebebasan berbicara, dan akhir dari korupsi yang merajalela.
Gerakan itu bermula dari duka, kematian Hu Yaobang, seorang tokoh reformis Partai Komunis yang dianggap bersimpati pada mahasiswa. Dari duka lahirlah keberanian, dan dari keberanian lahirlah tuntutan untuk sebuah masa depan yang lebih adil. Dalam hitungan minggu, Tiananmen menjelma menjadi simbol kebangkitan sipil di hadapan negara yang otoriter.
Namun, pada tanggal 3–4 Juni 1989, sejarah berbelok dengan cara paling tragis. Pemerintah mengerahkan tentara dan tank untuk mengosongkan lapangan. Gas air mata, peluru, dan rantai baja kendaraan lapis baja menutup wajah-wajah penuh harapan. Jumlah korban jiwa tidak pernah diumumkan secara resmi, tapi diperkirakan ratusan hingga ribuan. Dunia terkejut, sementara di dalam negeri, ingatan itu dipaksa hilang oleh sensor yang ketat.
Ikon abadi dari tragedi ini adalah “Tank Man”—seorang pria tanpa nama, membawa kantong belanja, berdiri seorang diri menghadang barisan tank. Sosoknya menjadi simbol keberanian individual menghadapi kekuasaan yang menindas. Gambar itu tersebar ke seluruh dunia, namun ironisnya, di tanah kelahirannya sendiri, ia dilarang untuk dikenang.
Bagi kita yang membaca kembali peristiwa ini, Tiananmen bukan hanya soal Tiongkok. Ia adalah cermin universal tentang pertanyaan kemanusiaan: apa harga dari kebebasan? Apa batas kekuasaan negara atas rakyatnya? Dan bagaimana kita, sebagai umat manusia, memastikan bahwa pengorbanan semacam itu tidak sia-sia?
Dalam tradisi Abrahamik, ada satu benang merah: Allah menuntut keadilan dan mengutuk kezaliman. Nabi Musa berdiri di hadapan Firaun, Nabi Isa bersuara bagi kaum tertindas, Nabi Muhammad menegakkan keadilan di tengah masyarakat Quraisy. Setiap kisah itu menegaskan satu hal: keberanian moral sering lahir dari kerentanan manusia yang tampak lemah, tapi justru itulah yang menggetarkan sejarah.
Tiananmen 1989 adalah saksi bahwa keinginan untuk merdeka dan bermartabat tidak pernah bisa sepenuhnya dipadamkan. Meski generasi baru di Tiongkok mungkin tidak lagi mengetahui detailnya, dunia tetap mengingat. Luka itu hidup dalam foto, kesaksian, dan doa mereka yang selamat.
Sejarah menuntut kita untuk tidak hanya mengenang, tetapi juga bertanya: ketika kekuasaan menutup ruang kebebasan, apakah kita akan diam, ataukah berdiri—meski seorang diri—seperti Tank Man?
Penulis: Abqurah