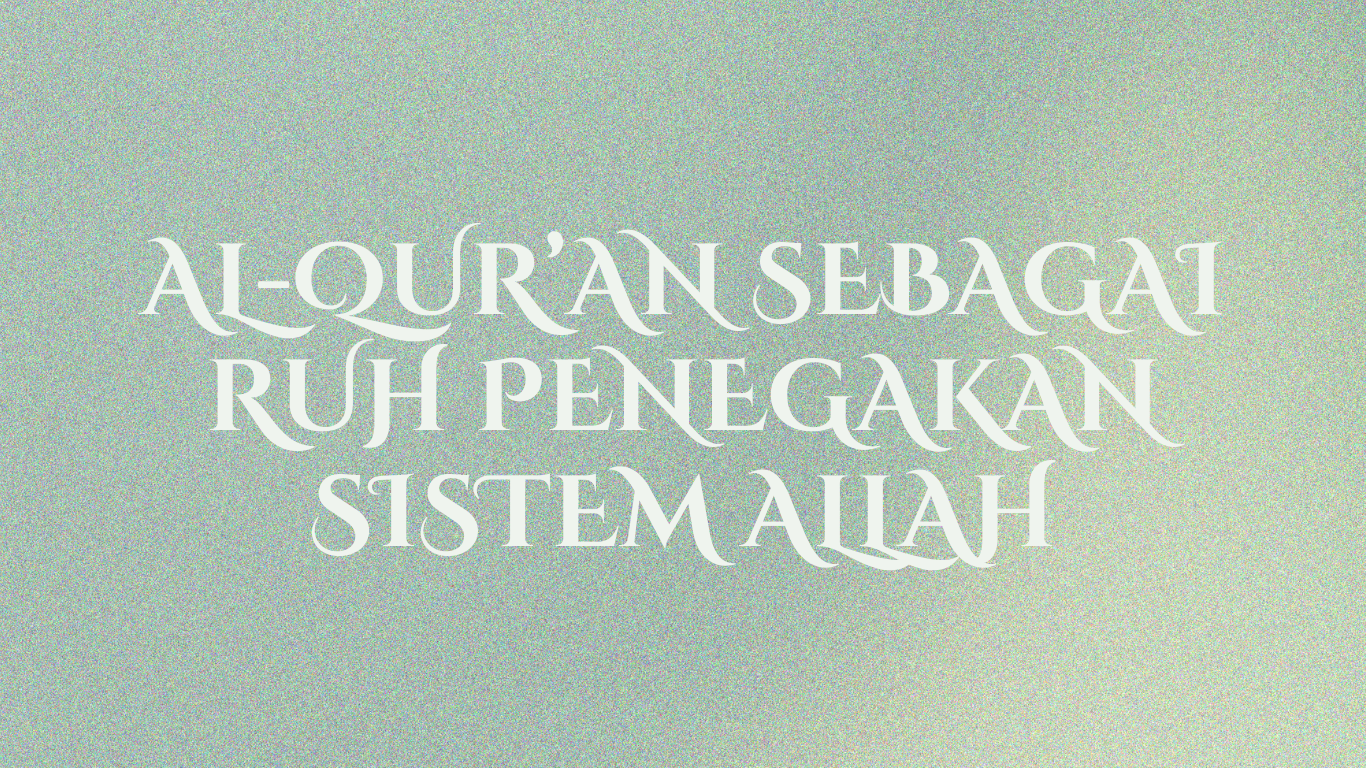Ada luka yang tidak mengeluarkan darah. Ada pula yang tak terlihat, tapi tetap terasa hingga menyesakkan. Di dunia yang terus bergerak cepat, penuh tekanan, perbandingan, dan tuntutan semakin banyak orang menyakiti dirinya sendiri bukan karena ingin kehilangan nyawa, tetapi karena ingin merasa hidup. Fenomena itu disebut self-harm.
Self-harm, atau perilaku menyakiti diri sendiri, adalah tindakan seseorang melukai tubuhnya secara sengaja, bukan untuk bunuh diri, tetapi untuk mengatasi rasa sakit emosional yang luar biasa. Bentuknya bisa bermacam-macam, menggores kulit dengan benda tajam, membenturkan kepala, memukul diri, membakar kulit, bahkan menahan rasa lapar ekstrem. Dalam bahasa psikologi, bentuk self-harm tanpa niat bunuh diri dikenal sebagai Non-Suicidal Self-Injury (NSSI). Menurut American Psychiatric Association (2022), NSSI merupakan salah satu respons maladaptif terhadap tekanan psikologis, sering muncul pada masa remaja hingga dewasa muda.
Banyak yang salah paham, menganggap self-harm sebagai “drama” atau “pencarian perhatian”. Padahal, penelitian justru menunjukkan hal sebaliknya: sebagian besar pelaku self-harm menyembunyikan luka mereka. Luka itu adalah bahasa diam dari pikiran yang lelah.
Sebuah studi di Frontiers in Psychiatry (2025) memperkirakan lebih dari 5,4 juta kasus baru self-harm terjadi di seluruh dunia pada tahun 2021, dan jumlah ini diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjelang 2040. Data ini tidak hanya angka tetapi cerminan dari krisis emosional yang kian meluas. Di Indonesia sendiri, survei nasional oleh Rofiah dkk. (2022) selama pandemi menunjukkan sekitar 15% responden pernah berpikir untuk menyakiti diri, dan 4% benar-benar melakukannya. Sebagian besar adalah remaja dan mahasiswa.
Di kalangan mahasiswa Indonesia, penelitian oleh Nurjanah & Putri (2023) menemukan bahwa 48,1% mahasiswa pernah melukai diri dalam bentuk apa pun, baik secara langsung (memotong, memukul diri) maupun tidak langsung (menolak makan, memaksa diri belajar berlebihan). Mereka bukan tidak tahu bahwa itu menyakitkan, justru karena terlalu sakit, mereka berusaha menyalurkan rasa itu ke luar.
Kita tidak berbicara tentang bunu* diri. Kita berbicara tentang bagaimana seseorang mencoba bertahan hidup dengan cara yang menyakitkan.
Dalam ilmu Psikologi klinis menyebut self-harm sebagai bentuk emotion regulation yaitu cara cepat meredam emosi yang intens seperti sedih, bersalah, marah, atau hampa. Saat seseorang merasa tidak punya kendali atas pikirannya, melukai diri memberi ilusi bahwa ia masih berkuasa atas tubuhnya. Sayangnya, kelegaan itu hanya sesaat. Setelahnya, datang rasa bersalah, malu, dan takut ketahuan. Lalu siklus itu berulang lagi.
Sebuah penelitian longitudinal di Tiongkok (Zhang et al., 2023) menunjukkan peningkatan signifikan perilaku self-harm pada remaja usia 10–17 tahun selama 2017–2021, terutama pada perempuan. Lonjakan paling tajam terjadi setelah masa pandemi. Isolasi sosial, tekanan akademik, dan perubahan emosi di usia remaja menjadi pemicu yang sulit dikendalikan.
Fenomena ini juga terjadi di Eropa. Di Spanyol, studi García-Carrasco et al. (2024) menemukan peningkatan kasus self-harm pada usia di bawah 25 tahun pasca pandemi COVID-19, dengan riwayat gangguan afektif dan penggunaan zat sebagai prediktor kuat perilaku berulang. Dalam banyak kasus, self-harm menjadi semacam “alarm emosional”, yaitu tanda bahwa seseorang butuh pertolongan, tapi tidak tahu bagaimana cara memintanya.
Yang menarik, banyak pelaku self-harm justru tampil “normal”: tersenyum di sekolah, berprestasi, bahkan aktif di media sosial. Namun di balik semua itu, ada kelelahan yang tak mereka tunjukkan. Sebuah studi besar di Inggris oleh Nature Scientific Reports (2023) menemukan bahwa 16,1% remaja pernah melakukan self-harm dalam satu tahun terakhir, dan perempuan (22,5%) lebih banyak daripada laki-laki (9,5%). Menariknya, sebagian besar tidak menceritakan hal ini pada siapa pun.
Faktor media sosial juga menjadi sorotan. Studi JMIR (2025) menyebut bahwa 83% remaja pernah melihat konten self-harm atau bunu* diri di media sosial, bahkan tanpa mencarinya. Paparan semacam ini dapat menormalkan perilaku berbahaya, membuat seseorang berpikir bahwa melukai diri adalah cara wajar menghadapi stres. Di Indonesia, paparan semacam itu makin mudah ditemui, baik di forum anonim, platform curhat, maupun unggahan estetika yang meromantisasi luka. Sebuah foto tangan berdara* bisa muncul di linimasa dengan caption lembut seperti puisi. Namun di baliknya, ada seseorang yang sedang berteriak diam-diam.
Psikologi modern memandang self-harm bukan sekadar gejala individual, tetapi sebagai manifestasi sosial dan emosional. Di baliknya ada trauma, ekspektasi, atau pengalaman ditolak.
Faktor-faktor yang sering muncul antara lain:
- Depresi dan kecemasan yang tidak tertangani
- Pengalaman kekerasan atau pelecehan
- Tekanan sosial dan akademik
- Kurangnya dukungan keluarga
- Perasaan terasing atau kesepian
Menurut World Health Organization (2023), self-harm sering menjadi indikator awal risiko bunu* diri, namun banyak yang berhenti di tahap melukai diri tanpa niat mengakhiri hidup. Itu sebabnya, memahami self-harm penting bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mendengar.
Ketika seseorang berkata, “Aku melukai diri,” yang sebenarnya ingin ia sampaikan adalah, “Aku sedang kesakitan, tapi tidak tahu cara lain untuk memberitahumu.” Pemulihan dari self-harm tidak mudah. Tapi bukan mustahil. Terapi kognitif perilaku (CBT) dan Dialectical Behavior Therapy (DBT) terbukti efektif membantu individu belajar mengelola emosi tanpa harus melukai diri. Dalam banyak studi (misalnya Lin et al., 2022; Crowell & Chen, 2023), intervensi berbasis kesadaran diri dan dukungan sosial berperan besar mengurangi perilaku ini.
Namun, penelitian juga menegaskan bahwa dukungan sosial adalah kunci. Mereka yang memiliki teman, keluarga, atau komunitas yang tidak menghakimi memiliki kemungkinan pemulihan lebih besar. Itu artinya, setiap orang bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan orang lain, bukan dengan nasihat panjang, tetapi dengan kehadiran yang tidak menghakimi.
Di tengah semua data dan teori, ada pesan sederhana yang sering terlupakan: setiap manusia bernilai. Ketika seseorang kehilangan tujuan dirinya, self-harm menjadi cara untuk “merasakan sesuatu”. Tapi tubuh bukan musuh, tubuh adalah saksi bisu perjuangan kita.
Dalam Al-Qur’an, ada ayat yang bisa menjadi pengingat:
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa 4:29)
Ayat ini bukan sekadar larangan, tetapi peringatan penuh kasih bahwa hidup dan dirimu sangat berharga.
Begitu pula dalam QS. Al-Baqarah 2:195
“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.”
Ayat-ayat ini seakan berkata, jangan hukum tubuhmu karena kesedihan yang belum kamu pahami.
Sementara dalam Efesus 5:29 disebutkan:
“Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memeliharanya dan merawatinya.”
Dan satu pengingat lembut lagi dari QS. Al-Qaf ayat 16:
“Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri.”
Kalimat-kalimat itu bisa menjadi alarm bahwa meski dunia terasa gelap, nilai dan tujuan hidupmu seharusnya tidak hilang.
Self-harm adalah bahasa diam dari jiwa yang ingin didengarkan. Dalam diam itu, ada permohonan agar seseorang mengerti: aku tidak sedang mencari mati; aku hanya ingin rasa sakit ini berhenti. Namun tubuh tidak diciptakan untuk disakiti. Tubuh adalah bagian dari diri yang juga butuh kasih. Sebagian besar Psikolog menyebut bahwa proses pulih dari self-harm mirip dengan membangun kembali kepercayaan: butuh waktu, pengertian, dan kejujuran. Orang yang pernah melukai diri tidak lemah. Mereka justru sangat kuat, karena di antara semua rasa sakit, mereka masih memilih untuk bertahan.
Dalam riset Journal of Mental Health (2024), individu yang berhasil pulih dari self-harm menggambarkan prosesnya bukan sebagai “berhenti melukai diri”, tetapi sebagai “belajar menyangi diri kembali”. Pemulihan bukan garis lurus, tapi perjalanan yang penuh liku. Kadang ada kemunduran, kadang ada kemajuan kecil yang tak terlihat. Tapi setiap langkah kecil menuju penyembuhan adalah kemenangan yang layak dirayakan.
Kita bisa mulai dengan satu hal sederhana, berhenti menyalahkan diri, berhenti menyembunyikan luka, dan mulai berbicara. Karena setiap kisah sakit yang diucapkan dengan jujur adalah langkah pertama menuju pemulihan.
Dan jika semua terasa berat, ingatlah ayat yang sederhana tapi penuh makna berikut:
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah 94:6)
Mungkin belum hari ini. Tapi akan ada hari di mana kamu melihat bekas luka itu, lalu berkata: Aku sudah melalui semuanya. Dan aku tetap hidup. Benar, self-harm bukan jalan keluar. Tapi mari kita agar bisa lebih berpikir bahwa tidak semua orang punya tempat untuk menumpahkan rasa sakitnya. Maka, jika kamu bisa menjadi satu telinga yang mau mendengar, kamu sudah menyelamatkan satu pikiran dari kehancuran
PENULIS : Reine KA
Daftar Pustaka
Zhang, L., et al. (2023). Increasing prevalence of self-harm among adolescents in China: A 5-year longitudinal study. BMC Psychiatry.
García-Carrasco, M., et al. (2024). Trends and risk factors of self-harm among Spanish youth after COVID-19.Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health.
Nurjanah, D., & Putri, A. (2023). Self-Harm Behavior among University Students in Indonesia. Core.ac.uk Repository.
Rofiah, A., et al. (2022). Predicting self-harm and suicide ideation during the COVID-19 pandemic in Indonesia.Frontiers in Psychology.
Lin, X., & Crowell, S. E. (2023). Dialectical behavior therapy for self-injury and emotion dysregulation: Current evidence and perspectives. Clinical Psychology Review.
Frontiers in Psychiatry. (2025). Global burden and projection of self-harm 1990–2040.
JMIR Mental Health. (2025). Exposure to online self-harm content among adolescents: A national survey.
Nature Scientific Reports. (2023). Prevalence and predictors of adolescent self-harm.
WHO (2023). Preventing self-harm and suicide: Global report. Geneva: World Health Organization.
Crowell, S., & Chen, P. (2024). Reframing self-harm recovery: Learning self-compassion through behavioral therapy. Journal of Mental Health.