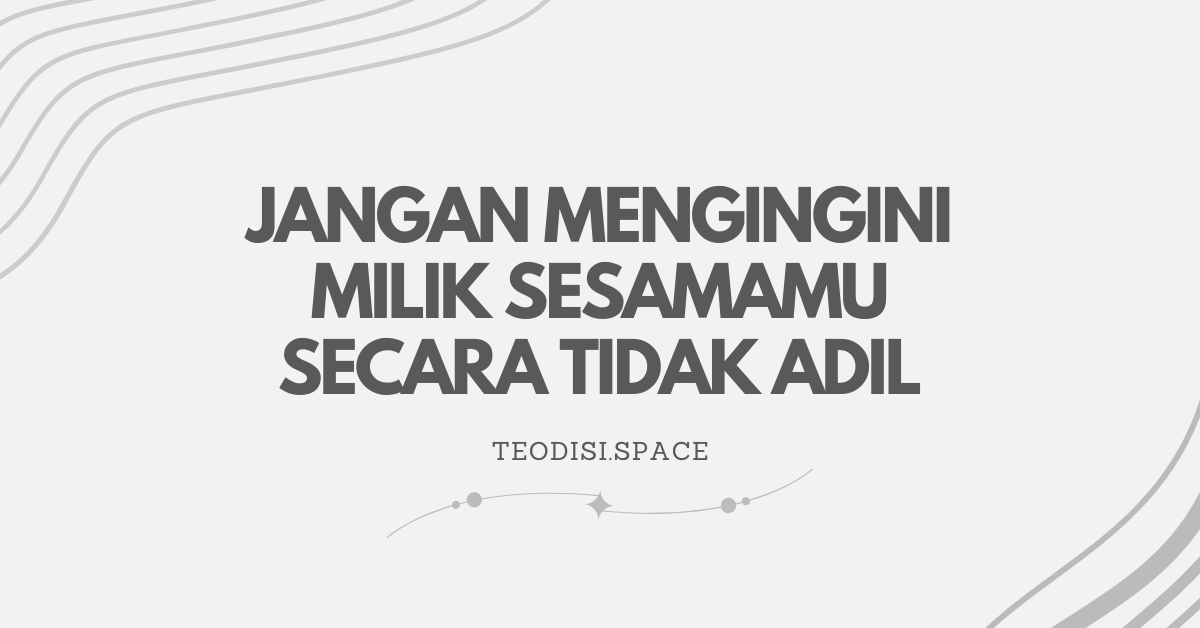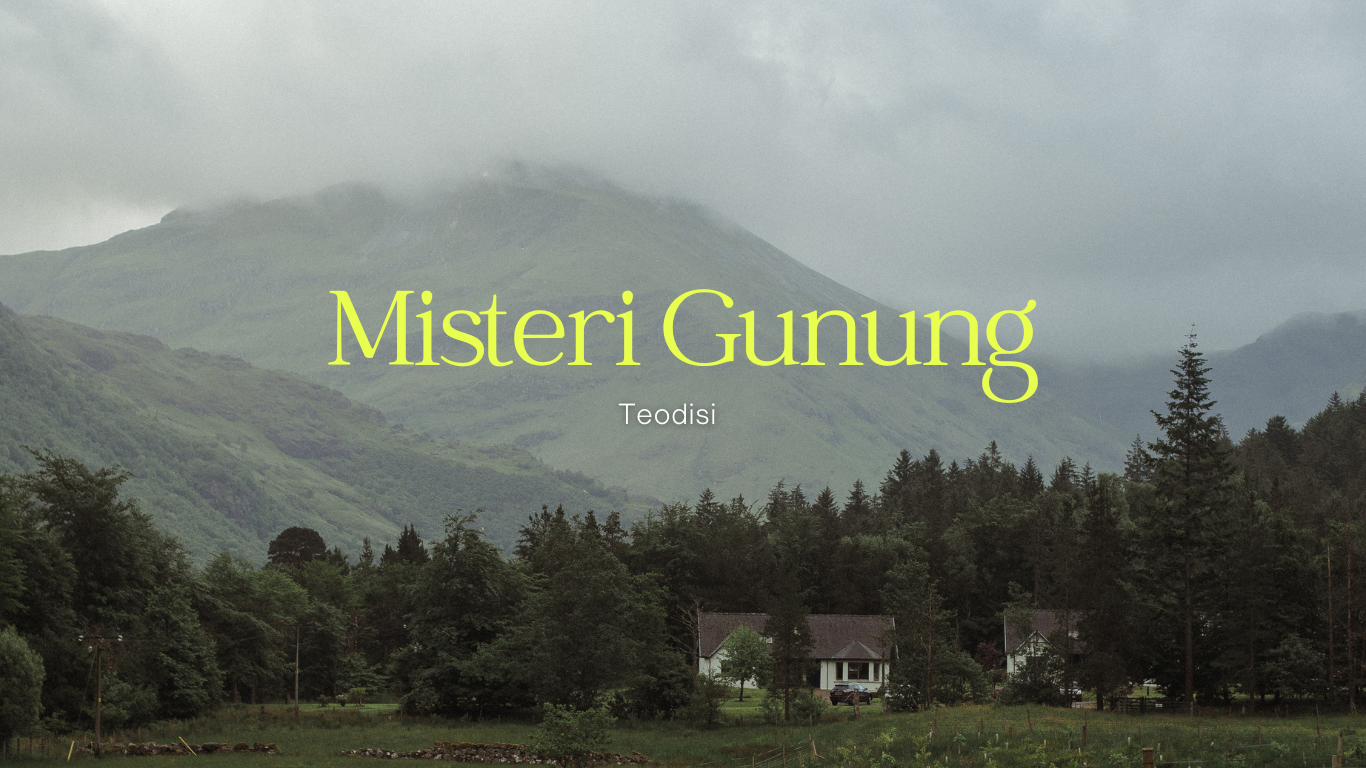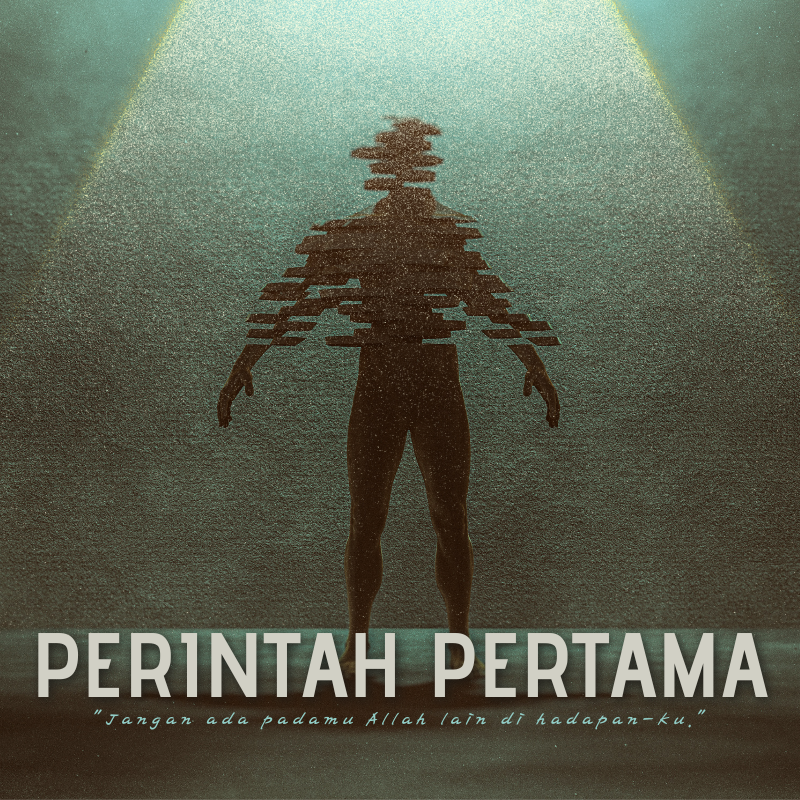Sinkretisme adalah sebuah proses atau fenomena penggabungan atau perpaduan dua atau lebih sistem kepercayaan, budaya, atau ideologi yang berbeda, sehingga melahirkan suatu bentuk baru yang menyatu. Istilah ini memang sering digunakan dalam konteks agama, tetapi sebenarnya juga dapat dijumpai dalam budaya, filsafat, bahkan politik sepanjang sejarah peradaban manusia.
Fenomena sinkretisme biasanya muncul karena adanya interaksi antar-masyarakat yang memiliki latar belakang kepercayaan atau pandangan hidup berbeda. Dalam banyak kasus, sinkretisme terjadi sebagai bentuk penyesuaian, penyederhanaan, atau upaya harmonisasi nilai-nilai yang dianggap berpotensi menimbulkan konflik, agar tercipta titik temu yang dapat diterima bersama. Namun, sinkretisme tidak selalu berarti melebur seluruh aspek ajaran yang berbeda secara utuh. Sering kali terjadi seleksi nilai atau simbol tertentu yang kemudian digabungkan demi tujuan sosial, politik, atau spiritual.
Dalam konteks agama, sinkretisme dapat terlihat pada banyak tradisi keagamaan yang lahir dari interaksi lintas budaya. Misalnya, dalam sejarah, banyak praktik keagamaan lokal yang bercampur dengan agama-agama besar saat agama tersebut menyebar ke wilayah baru. Unsur-unsur adat, bahasa, simbol, hingga ritual sering diadopsi agar ajaran baru lebih mudah diterima masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat beberapa agama atau aliran keagamaan tampak memiliki kemiripan simbolik atau praktik ibadah, meskipun berangkat dari sumber ajaran yang berbeda.
Di tengah fenomena sinkretisme tersebut, muncul pertanyaan menarik: Apakah setiap ajaran yang memiliki kemiripan satu sama lain otomatis dapat disebut sinkretis?
Pertanyaan ini menjadi semakin menarik saat kita menyinggung ajaran Nabi Ibrahim. Banyak orang beranggapan bahwa kemiripan unsur ajaran antara agama-agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam, menunjukkan adanya sinkretisme yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim. Hal tersebut karena ketiga agama tersebut sama-sama menempatkan figur Abraham/Ibrahim sebagai tokoh sentral, sebagai bapak leluhur.
Ajaran-ajaran dasar Nabi Ibrahim bukanlah bentuk sinkretisme agama, melainkan wujud dari dīn al-ḥaqq, yakni jalan kebenaran ciptaan Allah. Ajaran Ibrahim merupakan jalan hidup yang lurus dan murni, yang kemudian diteruskan oleh para nabi dan rasul sesudahnya, termasuk Nabi Muhammad, sebagai tuntunan hidup bagi manusia beriman agar menjadi umat yang diberkati, yaitu umat yang mendapatkan anugerah kekuasaan Allah (Kerajaan Allah) di muka bumi.
Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, surat An-Nahl ayat 123:
ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ṡumma auḥainā ilaika anittabi’ millata ibrāhīma ḥanīfā, wa mā kāna minal-musyrikīn
Artinya: “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): ‘Ikutilah Ajaran Ibrahim seorang yang hanif.’ Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.”
Dari sinilah muncul kembali pertanyaan yang sama: Apakah kesamaan ajaran di antara ketiga agama ini benar-benar akibat sinkretisme? Ataukah ada alasan historis dan wahyu yang lebih dalam yang menjelaskan hubungan mereka?
Untuk menjawabnya, kita perlu memahami lebih dulu bagaimana sejarah terbentuknya ketiga agama tersebut, serta bagaimana sebenarnya posisi para nabi dalam hubungannya dengan identitas keagamaan yang muncul kemudian.
Dari sisi sejarah, para ahli sepakat bahwa agama Yahudi, sebagai sebuah sistem kepercayaan yang terorganisir, belum benar-benar ada pada zaman Nabi Musa. Istilah “Yahudi” atau “Judaism” sebagai identitas agama baru banyak digunakan setelah peristiwa pembuangan ke Babilonia, yaitu sekitar abad ke-6 SM ke atas. Sebelum masa itu, orang-orang yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi lebih dikenal sebagai bangsa Israel atau Ibrani, bukan sebagai “orang Yahudi.”
Seorang penulis dan sejarawan agama, Karen Armstrong, dalam bukunya A History of God (2000), menjelaskan bahwa Judaism baru menjadi agama yang terstruktur lengkap dengan hukum, ibadah, dan kitab suci yang dikodifikasi setelah masa Ezra dan Nehemia, yang hidup sekitar abad ke-5 SM. Sementara itu, Nabi Musa hidup jauh sebelum masa itu, yakni sekitar abad ke-13 SM. Hal senada juga disampaikan oleh John J. Collins dalam bukunya Introduction to the Hebrew Bible (2014), yang mengatakan bahwa Judaism seperti yang kita kenal sekarang memang belum ada pada zaman Musa. Identitas keagamaan Yahudi lebih banyak muncul sebagai respons terhadap pengalaman besar bangsa Israel, seperti pembuangan ke Babilonia. Karena itulah, meskipun Nabi Musa adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah keagamaan Yahudi, ia tidak bisa serta-merta disebut sebagai “orang Yahudi” dalam pengertian agama Yahudi yang terlembaga setelah masa Ezra dan Nehemia.
Hal serupa juga terjadi dalam sejarah Kekristenan. Istilah Kristen baru mulai digunakan di Antiokhia, beberapa dekade setelah Nabi Isa (Yesus) wafat. Kisah Para Rasul 11:26 mencatat bahwa di Antiokhialah para pengikut Yesus pertama kali disebut “Christianoi” atau orang Kristen. Artinya, identitas Kristen sebagai sebuah komunitas yang terpisah dari Yahudi muncul setelah masa Yesus.
Bart D. Ehrman, seorang ahli sejarah Kekristenan awal, dalam bukunya The Triumph of Christianity (2018), menuliskan:
“Jesus himself was a Jew who practiced Judaism, and he did not start a new religion. The followers of Jesus, after his death, gradually formed a separate movement that became known as Christianity.”
Senada dengan itu, E.P. Sanders dalam The Historical Figure of Jesus (1993) menegaskan bahwa Yesus (Nabi Isa) adalah seorang yang taat, dan sama sekali tidak mendirikan agama baru bernama Kristen seperti yang kita kenal sekarang. Dari sudut pandang sejarah, agama Kristen sebagai institusi baru terbentuk secara bertahap setelah Nabi Isa wafat, seiring berkembangnya ajaran para pengikutnya. Karena itu, Nabi Isa tidak bisa langsung disebut sebagai “orang Kristen” dalam pengertian agama Kristen yang terstruktur kemudian hari.
Lalu bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Al-Qur’an dengan sangat tegas menyatakan bahwa Ibrahim bukan seorang Yahudi maupun seorang Nasrani, melainkan seorang yang lurus dan seorang Muslim yang hanif.
Dalam surat Ali ‘Imran ayat 67, dikatakan:
“Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, seorang muslim, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik.”
Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukanlah penganut Yahudi maupun Nasrani, melainkan seorang Muslim yang hanif, pengikut dīn al-Islām yang murni, yang tidak tercampur dengan ajaran lain. Karena itu, apabila ajaran Ibrahim dianggap sebagai bentuk sinkretisme, maka konsekuensinya Nabi Muhammad, yang oleh Al-Qur’an disebut paling dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim (QS Ali Imran ayat 68) juga harus dituduh melakukan sinkretisme?, padahal, Rasulullah secara tegas menyatakan dirinya sebagai pengikut ajaran Ibrahim yang lurus, bukan hasil pencampuran berbagai ajaran (QS An-Nahl ayat 123).
Dapat disimpulkan bahwa kesamaan unsur dalam agama-agama samawi bukanlah otomatis bukti terjadinya sinkretisme. Sebaliknya, banyak kemiripan tersebut berkaitan dengan akar sejarah yang sama dan nilai-nilai wahyu yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Sinkretisme memang merupakan realitas sosial-budaya yang terjadi di banyak peradaban manusia, tetapi tidak setiap ajaran yang tampak mirip dapat serta-merta dianggap sebagai hasil pencampuran ajaran yang berbeda.
Perlu diingat bahwa sinkretisme termasuk salah satu isme yang tidak selalu kompatibel, karena ia mencoba memadukan hal-hal yang kadang bersifat esensial dan mutlak berbeda. Hal ini membuat sinkretisme sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika prinsip-prinsip inti sebuah ajaran dianggap tercampur atau tersamarkan. Karena itu, meskipun sinkretisme kerap muncul sebagai solusi atas konflik atau perbedaan budaya, ia juga membawa tantangan besar dalam menjaga keaslian dan kemurnian suatu ajaran.
Penulis: Pamungkas
Editor & Konten: Reine